Agomo Budoyo
Oleh: Dahlan Iskan
.jpeg)
Ada empat mobil yang parkir di garasi terbukanya. Termasuk Alphard. Lalu ada masjid kecil di halaman depan. Bentuk masjidnya seperti kelenteng. Dibuat mirip masjid Cheng Hoo di Surabaya.
Kirun memang pernah ke masjid di Guangzhou, Tiongkok. Pandangannya tentang Tiongkok dan Islam berubah sejak dari sana. Ia juga ke Shenzhen: melihat bagaimana negara di sana melestarikan budaya Tiongkok. Ia menonton ludruk Tiongkok di Shenzhen. Di sana disebut cha guan.
Pandangan Kirun yang lapang juga lantaran Kirun banyak jalan ke berbagai negara. Juga ke berbagai daerah. Ia melihat begitu banyak perbedaan tanpa harus bermusuhan.
Kirun pernah empat tahun di Papua. Di Sorong. Di Manokwari. Di Jayapura. Waktu itu Kodam di sana –juga di provinsi lain– punya bagian kesenian untuk sosialisasi program-program pemerintah. Kirun menjadi pegawai sipil di Kodam. Dengan tugas utama di panggung-panggung kesenian.
"Menghidup-hidupkan kesenian" sudah menjadi prinsip dalam hidupnya. Kesenian telah memberinya hidup yang baik. Ia melihat alangkah keringnya kehidupan tanpa kesenian.
Di pemerintahan, katanya, generasi berganti. Di tentara terus berganti. Di tokoh-tokoh agama juga terus terjadi pergantian generasi. Kalau di kesenian tidak terjadi hal yang sama, kesenian ini akan punah. Lalu identitas bangsa ini akan ikut hilang.
Kirun hanya tamatan SMP. Di desa itu. Lalu main wayang orang. Ikut ketoprak. Ludruk. Dan apa saja. Salah satu dari dua anaknya baru saja lulus Institut Seni Indonesia Solo. Jurusan karawitan. Satunya lagi wanita, kawin dengan tentara.
"Kompleks padepokan ini luas sekali. Ada dua hektare?”
 JPNN.com
JPNN.com 
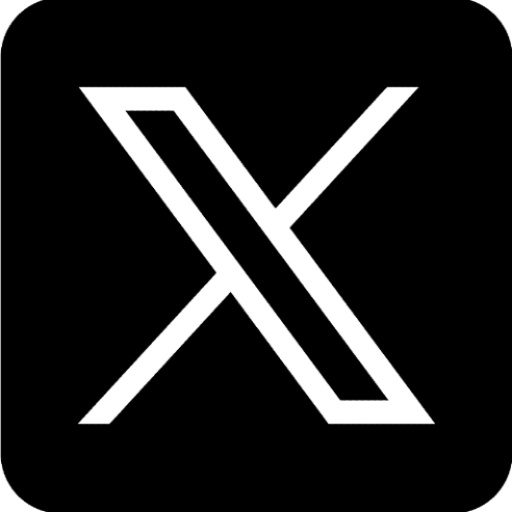







.jpeg)





