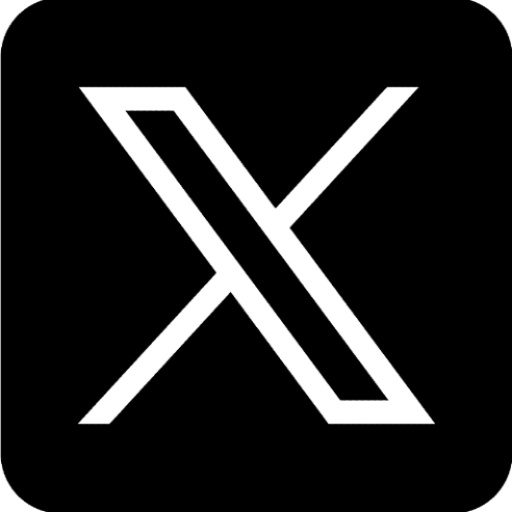Bangsa Pelupa dan Pemaaf, Sebuah Refleksi Tentang Karakter Kolektif Indonesia
Oleh: Drajat Wibowo, pemerhati sosial dan budaya, tinggal di Bali

Mengapa kita selalu lupa?
Kita bisa melihat kebiasaan ini dihapus dari sejarah panjang Nusantara. Sejak zaman kerajaan, pola yang sama terus berulang: konflik muncul, perlawanan terjadi, tetapi akhirnya selalu ada kompromi.
Pada masa Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan kecil yang memberontak jarang dihancurkan secara total.
Sebaliknya, kerajaan yang menang sering kali memilih jalur diplomasi, misalnya, dengan menikahkan anak raja sebagai bentuk rekonsiliasi. Pada akhirnya, konflik itu terhenti, tetapi tidak benar-benar selesai.
Ketika memasuki era Mataram Islam, terlihat bagaimana stabilitas menjadi prioritas utama. Kekuasaan raja begitu absolut sehingga tidak ada ruang bagi rakyat untuk memahami kebijakan atau mencari keadilan.
Budaya feodal ini menciptakan pola pikir bahwa rakyat sebaiknya menerima saja keadaannya daripada melawan sesuatu yang tidak bisa mereka ubah (Hofstede, 1980).
Lalu datanglah masa kolonial yang makin memperkuat mentalitas tersebut. Perlawanan terhadap penjajah sering kali berakhir dengan kekerasan dan penderitaan bagi rakyat. Akibatnya, masyarakat kian terbiasa menahan diri dan menghindari konfrontasi.
Setelah merdeka, apakah kita berubah? Tidak sepenuhnya.
Sejarah bangsa ini penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Kita pernah menyaksikan jatuhnya rezim, bangkitnya kekuatan baru, skandal besar yang menghebohkan.
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk
- Sejarah Etnik Simalungun dan Kepahlawanan Rondahaim Saragih
- Memaknai Peperangan di Padang Kurusetra Dalam Epos Mahabarata
- Tantangan Bangsa Berat, Barikade 98 Dorong Penguatan Komitmen Persatuan Nasional
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
 JPNN.com
JPNN.com