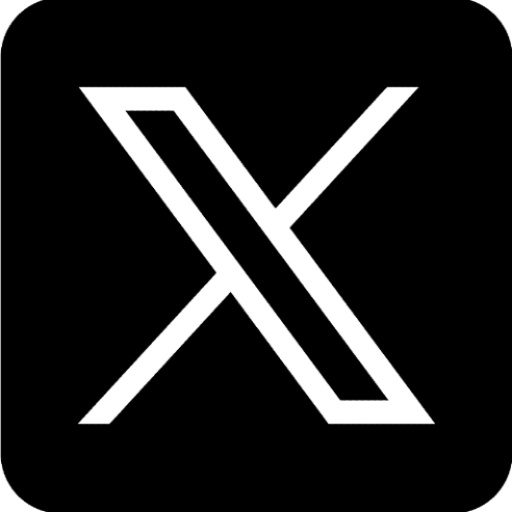Bermain Yoyo versus Bercermin Diri
Senin, 02 Februari 2009 – 16:14 WIB

Bermain Yoyo versus Bercermin Diri
Bulu kuduk saya, yang kala itu masih menjadi jurnalis pemula di Medan merinding. Saya bukan anggota GMNI. Tapi ada sesuatu yang mendebarkan dan menggetarkan tentang sebuah cita-cita yang lebih berharga ketimbang kursi DPR, menteri, bahkan tahta presiden sekalipun. Jika PNI kalah dalam Pemilu 1971, tak lain karena praktek demokrasi di era Orde Baru yang kelam itu.
Tapi politik tidak sekedar kepiawaian mengolah kata-kata. Tak dimungkiri kampanye harus punya daya gugah, walau tidak harus seperti iklan produk di televisi yang menggairahkan dan berlebihan. Kampanye tentang program dan masa depan bangsa yang bisa menjemukan di depan sebuah rapat raksasa yang hura-hura, ketika emosi lebih berperan ketimbang otak, seyogianya harus tetap menarik di tangan seorang politikus kawakan.
Partai yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan yang dianak-tirikan oleh rezim yang lebih mencintai konglomerat yang bahkan utangnya ditanggung BLBI (yang berasal dari pajak rakyat) dan menjadi beban berat yang membikin bahu rakyat semakin miring, benarkah kurang dielu-elukan publik? Senaif itukah rakyat, justru setelah sembilan kali Pemilu, dan 2009 ini yang kesepuluh?
Berseliweran anggapan bahwa rakyat tidak tahu apa apa yang terbaik bagi mereka. Rakyat, dalam persepsi sementara pemimpin seperti tampak pada Pemilu-Pemilu lalu hanya butuh artis yang bergoyang menghibur di pentas kampanye. Lalu, bagi-bagi kaos oblong, nasi bungkus dan, ehem-ehem, terselip helai-helai rupiah?
 JPNN.com
JPNN.com