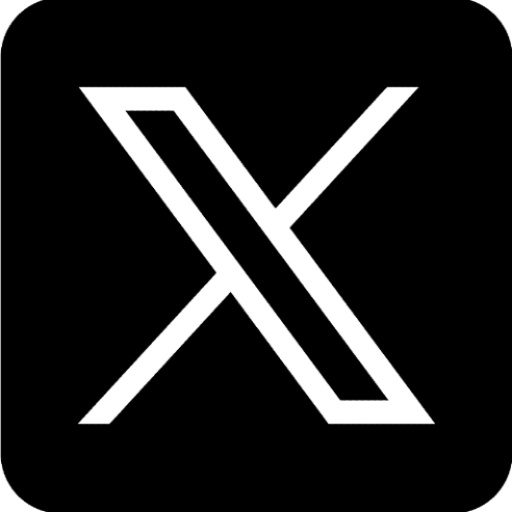Dengar Kiai Langitan, Bos Holcim Manggut-Manggut

jpnn.com - Seperti halnya Indonesia, Swiss juga menghadapi tantangan berat bagaimana mengelola kemajemukan masyarakatnya. Berikut catatan wartawan Jawa Pos MOHAMAD ELMAN yang selama sepekan lebih mengunjungi Swiss.
BUKAN hal aneh jika Patek Philippe, salah satu arloji terkemuka dunia, lebih senang menyebut dirinya sebagai produk Geneve (Jenewa). Bukan Swiss. Sebab, bagi Patek Philippe, mungkin, kalau cuma disebut Swiss Made terlalu umum. Keterkaitan citra korporasi dengan jati diri serta kultur kanton "semacam negara bagian di Swiss" Jenewa adalah hal penting.
Unity not Uniformity. Kesatuan bukan keseragaman. Semboyan itulah yang menjadi kebanggaan orang Swiss. Kesan itu pula yang saya rasakan selama di sana. Pagi sekitar pukul 09.00 setelah pesawat tiba di bandara Kota Zurich, sapaan selamat datang yang saya dengar dari petugas adalah willkommen. Bahasa Jerman memang menjadi bahasa utama di kota terbesar Swiss itu.
Kurang sejam kemudian, sesaat setelah pesawat penerbangan lokal saya mendarat di Bandara Jenewa, pegawai bandara menyapa dengan kata yang lain lagi: bonjour atau bienvenue. Kota ini memang bernuansa "Prancis banget". Saat berada di jalanan, mal, stasiun, atau naik feri di (danau) Lac Leman sulit membedakan apakah kita berada di Swiss atau Prancis.
Hampir semua petunjuk kota ditulis dalam bahasa tersebut. Secara geografis kanton (total ada 26 kanton di Swiss) memang dekat dengan Prancis, sehingga ada ribuan pekerja komuter yang ulang alik melintasi perbatasan saban hari. Jenewa yang merupakan kota terbesar nomor dua menjadi tempat markas PBB dan berbagai badan tingkat dunia, seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Palang Merah Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, dan lain-lain. Karena banyak ditinggali diplomat dan pekerja asing, warga Kota Jenewa dikenal toleran, terbuka, dan liberal.
Hampir seminggu saya mengikuti konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa, saya tinggal dan sering naik bus bersama delegasi dari Afrika. Banyak di antara mereka yang mengenakan baju terusan gombyor sampai kaki serta penutup kepala tradisional Afrika. Bagi warga Jenewa, pemandangan seperti itu adalah hal biasa.
Swiss yang berpenduduk sekitar 7,7 juta kini memang tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Negeri berbentuk konfederasi ini tetap memilih netral. Tidak mau bergabung dengan Uni Eropa serta mempertahankan mata uang sendiri: Swiss Frenc. Meski demikian, segalanya tak selalu berjalan "damai" di Swiss. Khususnya saat menghadapi pengaruh gelombang sentimen anti-Islam yang kini melanda Eropa.
Salah satu yang mendapat perhatian internasional adalah larangan pembangunan menara masjid di Swiss. Meski keputusan ini dihasilkan lewat referendum lebih tujuh bulan lalu, isu tersebut masih menjadi bahan diskusi yang hangat. Tak sedikit orang Swiss yang menganggap hasil referendum itu mencederai nilai-nilai luhur demokrasi mereka, khususnya penghargaan terhadap perbedaan.
Swiss juga menghadapi tantangan berat bagaimana mengelola kemajemukan masyarakatnya.
- Babak Baru Perang Dagang Dunia, Indonesia Jadi 'Sasaran Empuk'
- Gempa Myanmar, Indonesia Kirim Bantuan Tahap Tiga
- IDCI Nilai Pertahanan Siber Seharusnya Jadi Tugas Utama TNI
- AHY Dinilai Tepat Menunjuk Rezka Oktoberia Jadi Wasekjen Demokrat
- TB Hasanuddin Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dilindungi, Intimidasi Tak Bisa Ditolerasi
- Soal Kasus Hasto Kristiyanto, Pakar Nilai Langkah KPK Bermuatan Politis
 JPNN.com
JPNN.com