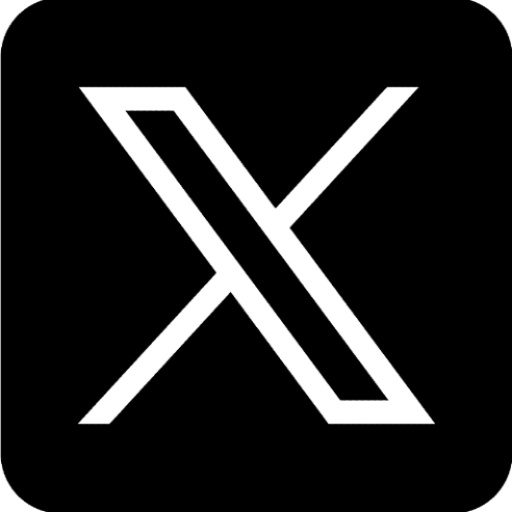Dieksekusi Cak Sakera di Hari Pemilu
Jumat, 09 Januari 2009 – 15:01 WIB

Dieksekusi Cak Sakera di Hari Pemilu
ALKISAH, seorang calon anggota legislative (caleg) dirundung resah gelisah semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa suara terbanyaklah yang menjadi king maker. Bukan daftar nomor urut. Ia kecut membayangkan harus bersaing dengan caleg separtai. Jika dulu yang menyoblos gambar partai akan diraih caleg nomor jidat (yang teratas), kini diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak, walaupun terpuruk di nomor sepatu (urutan bawah). “Sepatu” bisa lebih terhormat dibanding “jidat” adalah gejala dekonstruksi politik teranyar. Pada Pemilu 2009, setiap caleg sudah mengandaikan akan dikepung oleh para kompetitor, baik di kiri-kanan dan depan-belakang rekan separtai dan partai pesaing. Bingung yang mana “kawan” dan mana “lawan.” Tak heran jika banyak caleg kehilangan gairah menyumbang dana untuk kampanye partai. Yang telanjur memberi, tinggal mengurut dada. Yang sempat membayar separo agar ditempatkan di daftar urut jidat, kini menunggak karena merasa masalah nomor urut tak lagi efektif merebut kursi. Tak lagi rahasia, penyusunan nomor urut caleg selama ini, tak selalu ditentukan oleh kompotensi, ketokohan dan yang mengakar di tengah masyarakat. Bahkan, mungkin kerap terjadi karena kedekatan dan lobi dengan pengurus partai, dan terbuka kemungkinan “jual beli” daftar urut nomor “jidat” hingga “leher”, “bahu” dan “dada.”
Selayang pandang tampaknya posisi partai telah dibonsai oleh putusan MK itu. Tapi, tidak! Yang terjadi adalah kristalisasi, pemurnian partai. Partai yang selama ini hanya dikuasai untuk kepentingan elit tertentu, sehingga merugikan rakyat sebagai “pangeran” demokrasi, telah dikritisi dengan putusan MK itu.
Baca Juga:
Begitupun, dengan putusan MK itu, partai tetap saja eksis. Tetap saja yang berhak mengajukan daftar caleg maupun calon presiden/wakil presiden. Kecuali untuk keterpilihan caleg telah ditentukan oleh suara terbanyak. Partai sebagai wadah aspirasi rakyat, haruslah menghormati kedaulatan rakyat. Tidak ada partai tanpa rakyat, tidak ada demokrasi tanpa partai, dan tidak ada demokrasi tanpa rakyat.
Jika rakyat lebih berkuasa dibanding partai, tak perlu gundah gulana. Kondisi itu sudah berada di jalan yang benar, dan membuat partai menemukan jati dirinya yang murni sebagai pengemban amanat rakyat. Jika dibaratkan sebuah PT (perseroan terbatas), maka pemegang saham terbesar dalam partai adalah rakyat. Elit pengurus hanyalah sekedar para direksi dan komisaris yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal ini rakyat melalui pengurus daerah dan cabang-cabangnya.
Mungkin, karena masih di masa transisi, keterpilihan bukan karena nomor urut terasa telah menjebol tradisi partai. Padahal, tradisi itu justru berasal dari keputusan formal organisatoris partai, sehingga diangap wajar dan demokratis. Akibatnya partai menjadi feodalis dan elitis. Ketika diubah dengan putusan MK itu, tradisi partai itu kehilangan legitimasi dan hanya sekedar “macan kertas.”
Partai politik memang punya biografi, tradisi dan otonomi yang berdaulat. Tetapi pada akhirnya mereka tak bisa mengukir sejarah seenak jidat sendiri, tanpa mempertimbangkan bahwa hakikat demokrasi adalah one man one vote. Sinyalemen Ben Anderson tentang kesenjangan yang prinsip antara antara Barat sebagai negeri asal demokrasi dengan kosmologi yang feodal dan tradisional di Indonesia, pada akhirnya mengalami senjakala.
 JPNN.com
JPNN.com