Druze
Oleh Dahlan Iskan

Saya sendok pula acar zaitun itu. Betapa pun asin kecutnya.
Ternyata itulah nasi bulgur. Baru sekali ini saya akan makan bulgur.
Waktu saya kecil kata bulgur itu terkenal. Dan tercemar. Sudah sering saya mendengarnya. Orang desa ramai membicarakannya. Dengan nada menghina. Dan melecehkannya.
Waktu itu akhir zaman pemerintahan Bung Karno. Tidak ada bahan pangan. Kelaparan di mana-mana. Tidak ada beras.
Biasanya, kalau tidak ada beras, terpaksa makan nasi jagung. Tapi jagung juga tidak ada.
Biasanya kami masih bisa dapat bahan makanan yang terjelek: gaplek. Singkong yang dikeringkan. Lalu ditepungkan. Dibuat tiwul. Itulah ‘kasta’ makanan yang paling rendah.
Tapi, zaman itu, gaplek pun tidak ada. Pemerintah membagi sesuatu yang sangat asing. Untuk pegawai negeri. Disebut ‘beras bulgur’.
Orang desa sangat membencinya. Tidak enak di rasa. Terhina di dada. Istilah ‘sampai makan beras bulgur’ adalah menunjukkan betapa kelaparannya manusia.
 JPNN.com
JPNN.com 
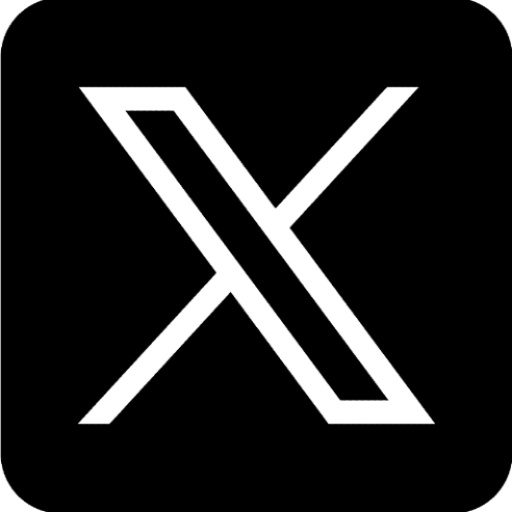







.jpeg)




