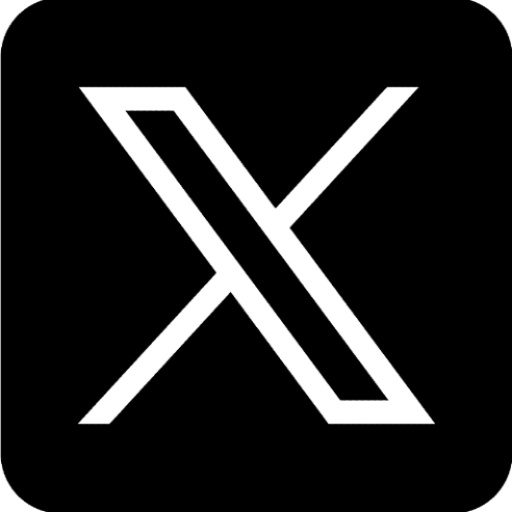Dulu Tak Berani Melintas, Kini Saling Menginap

Perempuan biasanya menjadi korban dalam konflik horizontal, baik menjadi korban langsung maupun kehilangan suami, anak, atau terusir dari rumah. Namun, di Poso, Sulawesi Tengah, para perempuan justru menjadi penyemai perdamaian dua kelompok yang berseberangan.
GUNAWAN SUTANTO, Poso
Tiga perempuan terlibat pembicaraan gayeng di pelataran toko kelontong di Desa Sayo, Kecamatan Poso Kota. Siang itu (11/4) Martince Baleona tengah bertamu ke rumah milik sahabatnya, seorang muslim, Yanti Udin. Di rumah Yanti hadir juga Mariani Lena.
Pembicaraan antarperempuan berbeda agama tersebut tak akan mungkin terlihat pada pertengahan 1990-an, saat desa itu menjadi front kelompok muslim dan kristiani yang sama-sama menjadi korban hasutan kelompok pendukung calon kepala daerah.
Konflik berlatar belakang agama secara formal memang telah berakhir. Namun, trauma dan rasa curiga masih membalut kedua pihak. Trauma umumnya dipicu adanya kerabat yang menjadi korban dalam konflik gara-gara ulah provokator dari luar Poso tersebut. "Konflik terbuka memang sudah sepakat diakhiri saat Deklarasi Malino pada 2001. Tapi, dendam dan kecurigaan masih lekat bertahun-tahun kemudian," ujar Martince.
Dia mengaku butuh waktu bertahun-tahun untuk menghapus trauma karena kematian salah seorang keponakan perempuannya yang menjadi korban mutilasi salah satu kelompok yang bertikai.
Perkenalannya dengan rekan-rekan yang berbeda agama di Sekolah Perempuan Mosintiwu membuatnya, juga ratusan perempuan korban konflik yang lain, mampu mengurangi trauma gara-gara konflik.
Sekolah itu didirikan Lian Gogali, aktivis perdamaian dan alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang tinggal di Tentana, desa di pinggir Danau Poso. Ketika sekolah itu didirikan pada 2006, luka memang seolah masih menganga. Desa-desa masih terpisah, desa muslim dan kristiani. Ketika itu tak ada seorang pun yang berbeda agama yang berani melintas di desa basis kelompok tertentu.
"Kalau mau ke pusat kota, seharusnya saya lewat sini karena lebih dekat. Tapi, saya memilih memutar daripada kena imbas," ujar Martince. Dia memang tinggal di Desa Bukit Bambu, desa berjarak 3 kilometer dari Sayo yang mayoritas dihuni kelompok kristiani.
"Saya kalau mau pulang kampung dari Poso ke Palopo juga sangat cemas jika lewat Tentena. Padahal, tidak ada jalan lain ke Palopo selain lewat Tentena," sambung Mariani Lena, penduduk Desa Sayo.
Rasa curiga pelan-pelan terkikis setelah para perempuan dari berbagai kampung dan latar belakang agama itu berinteraksi di kelas pembelajaran yang digalang Lian. "Ketika itu kita diajak ke berbagai tempat ibadah, bertemu pendeta dan ustad, menanyakan adakah ajaran untuk membunuh penganut agama lain," ujar Yanti. "Seumur hidup, saya juga baru kali itu ke masjid," sambung Martince, lantas tersenyum.
Lewat diskusi yang intens dengan berbagai pemuka agama dan tokoh masyarakat, pelan-pelan trauma yang menghinggapi Martince, Yanti, Mariani, dan ratusan peserta kelas perdamaian menghilang.
"Dari diskusi-diskusi dengan berbagai pemimpin agama itu, kami jadi tahu, tujuan semua agama itu sama. Ajaran agama dan praktik ibadah itu hanya jalan menuju Tuhan," ujar Martince.
Berbekal kesadaran tersebut, perempuan-perempuan itu menjadi agen-agen perdamaian di komunitas masing-masing. Secara tidak sadar, jaringan yang terbentuk membantu komunitasnya untuk menangkal isu penyerangan dari komunitas lain yang kala itu kerap menjadi momok.
Martince ingat, pada 2010 dirinya mendengar isu kampungnya akan diserang kelompok lain dari Sayo. Seisi Desa Bukit Bambu sudah bersiap dengan senjata untuk mempertahankan diri. Namun, Martince tak percaya isu tersebut. Dia segera mengontak Yanti, kawan sekolahnya yang tinggal di Sayo. Dia minta Yanti menelusuri kebenaran kabar itu.
"Yanti memastikan kabar tersebut tidak benar. Jadi, kami melihat apa yang terjadi selama ini hanya ulah orang yang memprovokasi untuk membangkitkan lagi dendam dan kecurigaan yang mungkin masih tersisa," terang Martince.
Para perempuan itu bahkan berusaha mencairkan kebekuan antarkampung dengan menggalakkan saling berkunjung antarsiswa sekolah. Kini Mariani tak ragu untuk menginap di rumah warga kristiani di Tentena bila hendak pulang ke daerah asalnya di Palopo.
Sebaliknya, warga Poso yang tinggal di dataran tinggi kerap menginap di rumah Mariani bila dalam perjalanan dari Poso Kota. "Jaraknya kan 60 kilometer, jalannya juga jelek. Jadi, kami biasa menginap di rumah kawan sekolah. Kami bisa begitu karena kecurigaan kami sudah tak ada karena disatukan di sekolah," terang Mariani.
Setelah menyemai benih perdamaian, ibu-ibu alumnus sekolah perempuan juga berupaya mengambil peran penting di kampungnya, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga. Kesadaran itu timbul karena di sekolah perempuan diajarkan keadilan gender yang mendorong perempuan lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di rumah tangga dan kampungnya.
Selepas sekolah perempuan, Yanti ditunjuk sebagai ketua rukun tetangga. Ketika amanah itu diterima, dia berjuang agar warganya yang kurang mampu menerima beras untuk masyarakat miskin (raskin). "Dulu mampu tidak mampu dapat raskin. Bahkan, PNS dapat raskin. Jumlahnya juga tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kini semua sudah tepat," terang Yanti.
Karena perannya yang menonjol, Yanti sempat diminta pengurus DPC PKB Poso untuk menjadi salah seorang caleg perempuan untuk mewakili daerah pemilihannya. Namun, karena belum memiliki pengalaman politik, dia menolak tawaran itu. "Saya masih butuh belajar politik," terangnya. Namun, tawaran menjadi caleg tersebut jelas sebuah kemajuan bagi seorang ibu yang sebelum ikut sekolah perempuan hanya sibuk mengurus rumah tangga sambil membuka toko kelontong kecil.
Lain lagi dengan Martince. Meski hanya mengenyam pendidikan formal sekolah dasar, dia kini terlibat dalam penelitian pengembangan kakao masyarakat Poso. Selama ini Poso memang penghasil kakao, namun masyarakat kurang mendapatkan manfaat karena pengolahannya dilakukan di kota lain. Atas penelitiannya itu, Martince sampai pernah diundang untuk memimpin rapat di hadapan pejabat Pemkab Poso.
Menurut Lian Gogali, Sekolah Perempuan Mosintuwu memang menerapkan sejumlah kurikulum terapan, yakni agama, toleransi dan perdamaian, gender, perempuan dan budaya, perempuan dan politik, keterampilan bicara dan nalar, hak layanan masyarakat, hak asasi manusia, serta ekonomi solidaritas.
"Sebelum mereka mengikuti sekolah ini, keberadaan ibu-ibu itu tidak diperhitungkan. Adat setempat bahkan menganggap perempuan itu karaya-raya (pamali) kalau terlibat urusan kampung," terang Lian.
Seperti Kartini yang mendirikan sekolah untuk para perempuan di Rembang guna mengangkat harkat perempuan, para Kartini di Poso juga tengah menyemai peradaban. (*/c10/noe)
Perempuan biasanya menjadi korban dalam konflik horizontal, baik menjadi korban langsung maupun kehilangan suami, anak, atau terusir dari rumah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Semarak Prosesi Paskah Semana Santa di Kota Reinha Rosari, Larantuka
- Sang Puspa Dunia Hiburan, Diusir saat Demam Malaria, Senantiasa Dekat Penguasa Istana
- Musala Al-Kautsar di Tepi Musi, Destinasi Wisata Religi Warisan Keturunan Wali
- Saat Hati Bhayangkara Sentuh Kalbu Yatim Piatu di Indragiri Hulu
- Kontroversi Rencana Penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer, Apresiasi Terhalang Stigma Kiri
- Kisah Jenderal Gondrong ke Iran demi Berantas Narkoba, Dijaga Ketat di Depan Kamar Hotel
 JPNN.com
JPNN.com