Faisal Basri
Oleh: Dahlan Iskan
.jpeg)
Tak lama kemudian ia keluar dari PAN. Saya menerima keputusan ini dengan sepenuh maklum. Dia pasti lebih produktif sebagai pengamat ekonomi yang tekun dan tajam, seperti cirinya yang semakin kita kenal. Namun dia, karena desakan banyak sahabatnya, sempat tergoda lagi dan mencoba bertarung di pilkada Jakarta.
Pengalaman ini tampaknya semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa politik, setidaknya bagi seorang yang mudah menangis seperti dia, memang bukan arena yang tepat untuk mengaktualkan bakat terbesarnya.
Tempat terbaik baginya adalah lapangan riset dan advokasi ekonomi. Dan di sektor ini dia menanamkan tonggak kuat di banyak lembaga penelitian –LPPM UI, Indef, ICW, dan lain-lain.
Dia bukan hanya menjadi suara ide ekonomi yang tajam, tetapi juga sebuah suara moral tentang keadilan sosial; suatu suara moral yang terutama bukan dia landaskan pada kitab etika umum, namun pada rasionalitas, pada pengetahuan dan pemahamannya yang kuat tentang cara terbaik bagi suatu negara dalam mengelola ekonomi nasional yang adil.
Beberapa tahun terakhir vokalnya terdengar semakin parau dan kritik-kritiknya semakin gamblang. Dia mengungkapkan ketaksabarannya yang kian tak tertahankan. Dia meneriakkan ketidakmengertiannya dengan emosional, kenapa ekonomi nasional dikelola dengan cara-cara yang baginya sangat merugikan Indonesia secara tak masuk akal.
***
Ketika pagi ini mendengar dia wafat, yang segera tergambar dalam lansekap kenangan saya bukanlah penampilannya yang sebersahaja dulu, dengan topi golf sebagai personal statement tambahan, tetapi suasana di suatu senja di sebuah vila di Puncak. Beristirahat dari rapat persiapan program PAN di Puncak untuk salat Magrib, jamaah 4-5 orang sepakat memintanya menjadi imam.
Kami semua terkejut. Dia memimpin salat dengan qiraah yang sangat baik. Vokal tenornya yang lirih dan fasih menjadi satu-satunya suara yang terdengar di senja yang sunyi senyap itu. Semua yang ikut menjadi makmumnya bisa merasakan energi kebaikan yang muncul dari keotentikan suaranya.
KAMIS kemarin itu sebenarnya Dr Faisal Basri punya jadwal ke pengadilan negeri Jakarta. Bersama tokoh pers Bambang Harymurti. Dua orang itu akan menjadi saksi.
- Mobil Handphone
- Korban Kedua Perahu Getek Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Lansia yang Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
- Tarif Tarifan
- Cici Faramida Mengenang Pesan Terakhir Sang Ibunda
- Kenang Sang Ibunda, Cici Faramida: Ibu Itu Hatinya Ingin Sekali Memberikan Kesenangan
 JPNN.com
JPNN.com 
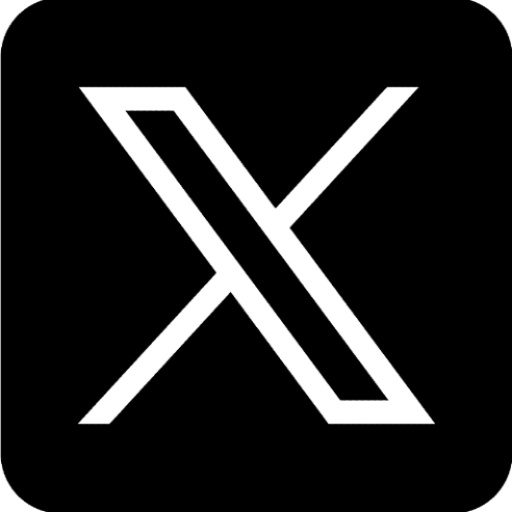




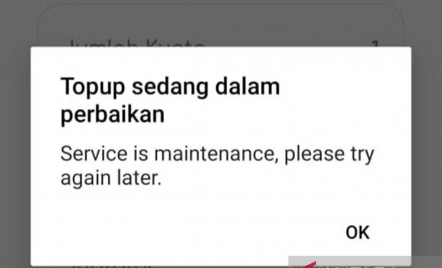






.jpeg)

