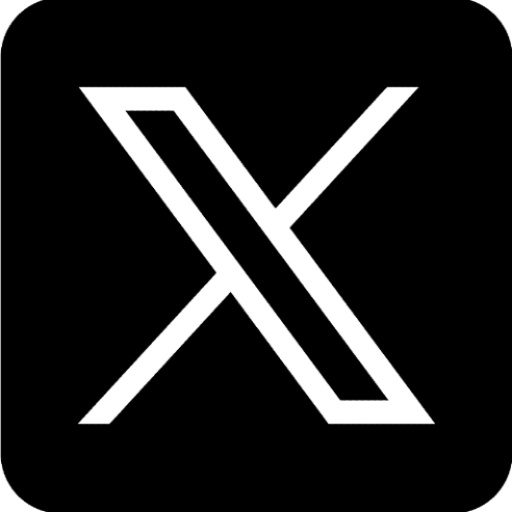Ingat Ayah di Senam Puasa
Oleh Dahlan Iskan

Belakangan ayah tidak mencangkul lagi. Sawah itu dijual. Setelah tidak ada meja dan lemari yang bisa dijual lagi. Ketika isi rumah sudah habis dijual. Ketika sakitnya ibu terus berlarut-larut.
Jadi, dibanding beratnya ayah mencangkul, di mana susahnya senam? Yang hanya 1,5 jam? Di bawah pohon rindang? Dengan lagu-lagu top hit bervariasi? Dengan teman-teman dansa yang sebagian seksi-seksi?
”Maka,” kata saya kepada peserta senam di bulan puasa, ”kalau Anda takut senam, ingatlah ayah saya.”
Dari sawah ayah mampir ke parit. Untuk mandi. Tepatnya untuk membersihkan badannya dari lumpur. Dengan segenggam rumput sebagai penggosoknya. Saya sering ikut seperti itu.
Tiba di rumah, ayah menggelar tikar mendong. Di lantai rumah yang berupa tanah. Tidur. Dengan celana kombor hitam lainnya. Tanpa baju. Saat telentang, terlihat kulit perutnya seperti menempel di bagian paling belakang tulangnya. Hanya turun naik napasnya yang menandakan kulit perut itu tidak lengket di dasar perutnya.
Satu jam kemudian ayah saya sudah di masjid: salat Duhur. Lalu ambil cangkul lagi ke sebidang tanah di belakang rumah. Atau sabit. Merapikan pohon pisang. Atau membetulkan parit. Atau menimba air sumur untuk mengisi bak mandi. Ada saja yang dilakukannya. Sampai azan Asar. Ke masjid. Jadi imam.
Pulang dari masjid langsung buka Alquran. Membacanya sampai senja. Satu bulan puasa ayah bisa tamat dua kali. Saya satu kali. Ayahlah yang dulu mengajari saya membaca Quran.
Sebelum masuk SD, saya sudah bisa menamatkannya. Saya sudah bisa membaca huruf Arab sebelum bisa membaca huruf Latin. Meski tidak tahu artinya. Tidak ada TK di desa saat itu. Apalagi playgroup.
 JPNN.com
JPNN.com