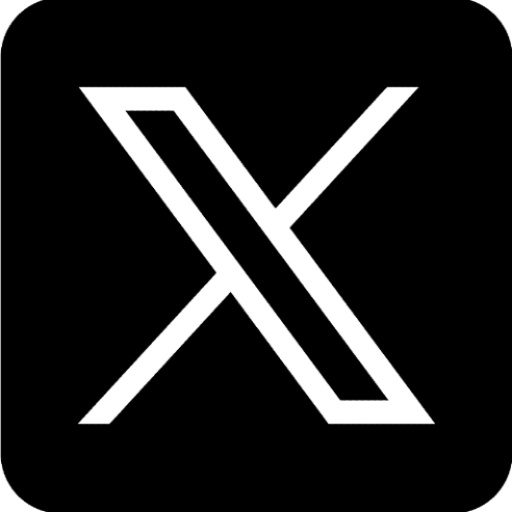Kisah Spiritual: Dari Laku Kebatinan, Belajar Nilai Islam
Oleh: Prof Dr dr Sardjana SpOG(K)SH NSL

Saya gandrung demokrasi dan sadar akan kebhinekaan etnis, agama, dan corak pemikiran dalam masyarakat kita, tapi mengapa kita tak cukup longgar mendengar argumen lain yang tak sejalan dengan kita? Mengapa kita tak sabar menghadapi kebhinekaan? ”Kalau mau serba seragam, lebih baik jadilah pembuat batu bata.”
Keseragaman memang mengesankan berfungsinya mesin rekayasa yang otoriter, kaku, dan dingin, mirip teriak kebulatan tekad yang mekanistis. Saya lebih suka kebhinekaan, tapi dalam kebhinekaan ada cacat yang tak saya sukai. Di sini orang bisa, dan mungkin mudah, tergelincir ke dalam kotak fanatisme yang selalu siap mengurung kita.
Sebaliknya, ungkapan semacam itu –pada hemat BJ Boland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1982)– ”hanya merupakan perwujudan dari perasaan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa”.
Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran, yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bid’ah.
Ibn Al-‘Arabi (1076-1148) mendendangkan kesadaran yang sama, ”Laqad shara qalbiy qabilan kulla shuratin, famar’a lighazlanin wa diir liruhbanin wa baytun li autsanin wa ka’batu thaifi wal wahu tawrati wa mushafu qur’anin” (Hatiku telah siap menerima segala simbol, apakah itu biara rahib-rahib Kristen, rumah berhala, Kakbah untuk thawaf, lembaran Taurat atau mushaf Al Quran).
Ketika menerima gelar Guru Besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009, saya diwawancarai dan menjawab bahwa tauhid yang dianut saya sebagai Panteis-monoteis.
Saya yakin bahwa Tuhan itu satu, tetapi Dia hadir dan berada di mana-mana. Tentu saja di kalangan Islam dan Kristen, istilah panteisme ini bisa mengundang salah paham. Kontan saja, orang langsung menghubungkannya dengan sosok legendaris Syekh Siti Jenar, ”Al-Hallaj”-nya orang Jawa.
Dalam berbagai kesempatan, saya menyitir paham kalam Asy’ariyah mengenai ketidakcukupan 20 sifat Allah, berbareng dengan kritiknya terhadap paham taqlid dan kejumudan-kejumudan kaum tradisionalis pada zamannya.
 JPNN.com
JPNN.com