Mempersoalkan Kehancuran Independensi KPK
Oleh: Anton Doni

Selanjutnya,(4) Status keuangan dan tunjangan pegawai KPK diatur realistik sedemikian rupa sehingga dapat menahan godaan yang melekat dalam tugasnya; (5) Bentuk dan proses-proses perijinan yang berlaku dalam hukum acara normal tetapi berpotensi menghambat pelaksanaan tugas ditiadakan; (6) Proses pembentukan dan penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas berlangsung dalam proses yang independen —tidak melalui pelatihan standar sebelumnya-- tanpa mengabaikan standar kompetensi-kompetensi utama kepenyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; (7) Kewenangan yang berpotensi terbesar untuk dikorupsi dan disalahgunakan dihindari, misalnya kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).
Ketujuh elemen independensi tersebut telah membentuk jati diri KPK yang relatif independen dan kuat, yang bisa saja dipandang positif karena daya dobraknya yang luar biasa, tetapi sebaliknya juga dipandang negatif oleh sebagian orang karena dirasakan sebagai superbody yang lepas dari kontrol siapapun. Baik tentang positif negatifnya atau murni tidaknya daya dobrak KPK maupun tentang positif negatifnya atau benar tidaknya KPK telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah superbody, sampai sejauh ini belum ada pengujian akademis yang relatif sistematis tentang itu. Namun di tengah penilaian-penilaian dan kesan-kesan tanpa validasi akademis tersebut, dilangsungkanlah proses revisi UU KPK dan menghasilkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kami sendiri mencatat, bahwa dalam proses revisi UU KPK, berkembang wacana tentang sejumlah persoalan yang berkaitan dengan eksistensi KPK, yang memperkuat dukungan bagi proses revisi UU KPK tersebut. Pertama, keadilan dalam penanganan persoalan korupsi; bahwa beberapa persoalan korupsi besar sepertinya terabaikan; dan bahwa sepertinya penanganan persoalan korupsi bersifat tebang pilih. Kedua, terlalu terbatasnya capaian KPK; yang kelihatan dari fokusnya KPK hanya pada satu tugas, sementara tugas yang lain sebagaimana diamanatkan Undang-Undang diabaikan.
Ketiga, kelalaian KPK dalam melaksanakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang; misalnya kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan. Keempat, ancaman terhadap hak-hak privat yang hadir dalam kerja KPK; bahwa penyadapan yang dilakukan dapat pula merekam urusan-urusan lain di luar korupsi, dan bahwa hasil rekaman tersebut tidak cukup pasti apakah dihanguskan atau tersimpan dan disalahgunakan. Kelima, potensi pendayagunaan lembaga KPK untuk kepentingan politis lain dan kepentingan ideologis yang tidak sejalan dengan Pancasila. Dan keenam, kecenderungan berkembangnya KPK sebagai super body, yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun.
Namun demikian, pencermatan kami terhadap isi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 hasil revisi memperlihatkan bahwa UU tersebut mengabaikan keperluan untuk menjawab persoalan-peroalan tersebut secara memadai, dengan terlebih dahulu mendasarkan diri pada suatu kajian akademis yang memadai, melainkan justru sebaliknya menghancurkan independensi KPK melalui perubahan terhadap pasal-pasal yang relevan.
Sehingga pertanyaannnya adalah apakah kita tidak lagi membutuhkan KPK sebagai suatu lembaga negara independen? Apakah basis asumsi tentang keperluan akan KPK sebagai sebuah lembaga negara independen sebagaimana yang kami sampaikan pada awal tulisan ini tidak relevan lagi? Apakah persoalan korupsi tidak lagi serius dan sudah tidak kita pandang lagi sebagai kejahatan luar biasa yang harus direspon dengan langkah luar biasa? Apakah lingkungan birokrasi secara umum sudah sehat, dan bahwa tanpa ada KPK yang melakukan kontrol dengan ketat, birokrasi dapat bekerja dengan integritas yang baik tanpa penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme? Apakah integritas kejaksaan dan kepolisian sudah dapat diandalkan, bahwa tanpa KPK kedua lembaga tersebut dapat berkerja dengan profesionalitas dan integritas tinggi?
Data menunjukkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang mengalami kenaikan, namun terlalu kecil, dari 37 menjadi 38 pada 2018. Indeks tersebut hanya menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih terlalu ngotot. Di bawah ancaman OTT (operasi tangkap tangan), toh masih ada 124 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2004 hingga 2019;. ada 103 orang anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi di tahun 2018, termasuk di dalamnya Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan korupsi secara berjamaah 41 anggota DPRD Kota Malang; dan ada ratusan perkara korupsi dana desa, dengan setidaknya 15-an pola korupsi, sebagaimana ditemukan ICW (Indonesian Corruption Watch). Data-data tersebut lebih menggambarkan seriusnya persoalan korupsi ketimbang kegagalan KPK.
Lalu bagaimana dengan kondisi birokrasi di Indonesia? Berdasarkan data ICW sejak 2004 sampai semester II 2016, birokrasi menduduki urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia, dengan beberapa modus korupsi seperti pemerasan, manipulasi tender, penganggaran fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku. Memang faktor utama korupsi adanya tekanan eksternal dari atasan, tetapi kondisi ini menggambarkan bahwa keadaan korupsi di lingkungan birokrasi di Indonesia tidak bisa kita anggap sudah aman. Apapun penyebabnya.
Penilaian bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di Asia juga merupakan penilaian yang merepresentasikan kondisi birokrasi di Indonesia.
- 5 Berita Terpopuler: Lisa Mariana Dipolisikan Ridwan Kamil, Sejumlah Aset Disita, Fakta Terungkap
- Sepeda Motor yang Disita KPK Sudah Tidak Ada di Rumah Ridwan Kamil
- KPK Datangi Rumah Ridwan Kamil Lagi, Aset Ini Disita
- Doktor Cumlaude Trimedya Dorong Optimalisasi Pengelolaan Barang Sitaan
- Pakar Hukum UI Nilai KPK Terkesan Targetkan untuk Menjerat La Nyalla
- Baru Menang Tender, Kontraktor Dimintai Rp 500 Juta, Alamak
 JPNN.com
JPNN.com 
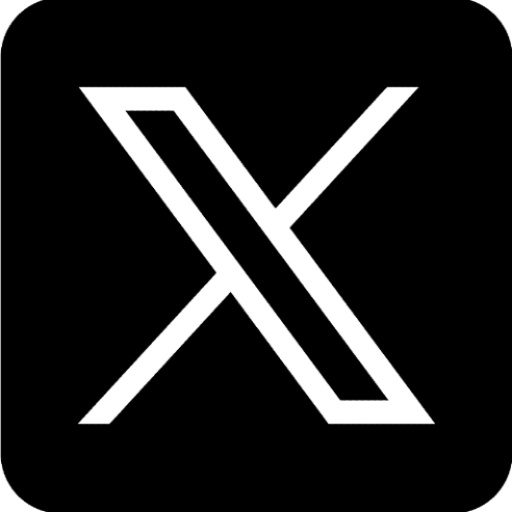







.jpeg)




