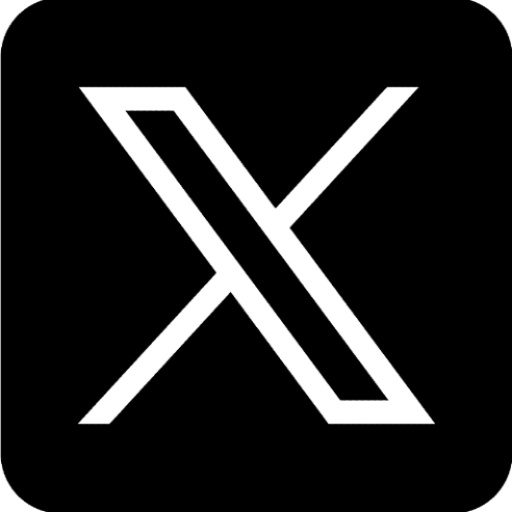Pradaksina, Gajah di Candi Muara Takus Menjalankan Ritual Buddha?

jpnn.com - Angin kelana rupanya mengarah ke Candi Muara Takus, Riau. Kisah dari masa lampau menyeru. Tiap purnama tiba, rombongan gajah datang mengelilingi stupa, dan lalu berlutut.
Wenri Wanhar – Jawa Pos National Network
Baru saja memasuki pekarangan Candi Muara Takus, Minggu, 27 Januari 2019, saya disambangi seorang anak muda. Dia memperkenalkan diri sebagai petugas BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya.
Namanya Izul. Dengan ramah dia menerangkan bahwa tempo hari ada penggalian. Tak jauh dari luar pagar candi, sebelah timur. Antara lain, yang ditemukan arca Ganesha.
Dari sedikit banyak yang saya kita ketahui, Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan. Wujudnya manusia berkepala gajah. Dengan belalainya, ia menghirup ilmu pengetahuan. Gadingnya yang sebelah dia patahkan, untuk menulis.
Saya lantas teringat cerita sayup-sayup tentang pradaksina gajah di Candi Muara Takus; tiap bulan purnama, serombongan gajah datang ramai-ramai.
Gajah-gajah itu berjalan mengelilingi candi, searah jarum jam. Seperti pradaksina, ibadah umat Buddha.
Setelah keliling, gajah-gajah itu diam. Berlama-lama mematut-matut candi, dan kemudian berlutut.
Dan kisah itu, kemarin, saya dengar langsung di pekarangan Candi Muara Takus. Dituturkan oleh sejumlah warga setempat. Saksi mata.
“Saya lihat langsung,” kata Izul, warga setempat yang bertugas menjaga candi, kepada JPNN.
Menurut Izul, karena penasaran, sekali waktu pernah datang orang Thailand membawa gajah dari negeri mereka ke Candi Muara Takus.
Eh, gajahnya langsung pradaksina. “Dan tak mau dibawa pulang lagi ke Thailand,” imbuh Izul sembari tertawa.
Kisah serupa tersua pula dalam catatan lawas pegawai kolonial Belanda dari tahun 1930-an.
Pada 1935, atas biaya dari Royal Netherlands Geographical Society, F.M. Schnitger, ilmuwan Belanda mengeksplorasi hutan Muara Takus, tepi Sungai Kampar Kanan.
“During the excavations of April, 1935, we were able to verify this strange phenomenon from personal experience,” tulis Schnitger dalam buku Forgotten Kingdom in Sumatra.
Schnitger bukan sembarang orang. Dia menyandang titel PH.D dan memangku jabatan conservator of the Museum at Palembang and Leader of the Archaelogical and Anthropological Expeditions in Sumatra.
Seperti apa pengalaman pribadi Schnitger, yang katanya, menyaksikan fenomena aneh di Candi Muara Takus?
Berikut sedikit banyak kami sari-terjemahkan dari sumber primernya...
Sudah seminggu lamanya kami berkemah di hutan Moeara Takoes, yang terletak di Kampar, sebuah sungai yang melengkung di sekitar garis khatulistiwa seperti gulungan ular besar.
Di sini sepi. Bulan purnama memancarkan cahaya yang aneh dan menyeramkan di atas reruntuhan (candi--red).
"Tuan," kata pelayan saya, dengan lembut. "Saya takut."
"Takut?" tanyaku, heran.
“Ya, ketika bulan purnama menyinari, gajah menyeberangi sungai dan pergi ke kuil suci. Kemudian mereka berkumpul melingkari menara tinggi dan berlutut sebagai penghormatan kepada roh raja mereka yang mati, yang terkubur di sana..."
Diam. Malam agung. Jangkrik-jangkrik bernyanyi dan suara mereka berbaur dengan gumaman sungai.
Menelaah catatan itu, nampak jelas bahwa mulanya, bagi Schnitger itu hanyalah bualan orang Timur.
“Kita di sini bukan untuk bermimpi, tetapi untuk menggali. Dan itu adalah kerja keras. Besok akan menjadi hari yang sibuk, karena gerbang yang baru saja saya temukan di dinding utara yang mengelilingi bangunan candi harus dibersihkan dan diukur,” tandasnya seraya membentangkan tikar tidur di tanah dan berbaring.
Saya mengantuk. Sungai menyanyikanku dengan lembut untuk tidur.
Sudah lewat tengah malam ketika saya terbangun dengan kaget. Di sekelilingku berdiri sekelompok penduduk asli.
Midon, pekerja terbaikku, membungkuk padaku. Lipatan serban putihnya menyapu wajahku. Di tangannya dia memegang senapan besar dan kuno.
“Semoga tuan memaafkan saya. Awalnya kami tidak ingin membangunkan Anda, tetapi sekarang...”
Seketika itu, dari hutan terdengar raungan. Suaranya belum pernah kudengar. Jantung yang gagahpun dibuat bergetar.
“Di desa, kami mendengar terompet dan raungan gajah. Mereka turun dari Gunung Suliki yang berkabut. Mereka menyeberangi sungai, langsung menuju ke rumah tuan. Kemudian kami takut dan ingat bahwa tuan itu sendirian..."
“Lalu,” aku memotong, tidak sabar. "Di mana mereka sekarang?"
"Mereka perlahan mendekat. Dalam seperempat jam mereka mungkin ada di sini. Kita tidak bisa melarikan diri. "
Dengan susah payah saya memusatkan pikiran saya dan mencoba menghitung peluang untuk melarikan diri.
Jika kita berada di pelataran bangunan suci, di atas reruntuhan tertinggi kita akan aman. Tapi bagaimana menuju ke sana? Jarak dari rumah adalah sekitar 100 m.
Sekencang-kencangnya lari, tidak akan mungkin.
Dalam imajinasi, saya sudah melihat gajah berlari keluar dari semak-semak!
Namun masih ada kemungkinan lain. Di dekat pondok, Kampar memiliki tebing yang curam dan menurun tiba-tiba. Tidak ada gajah yang berani memanjat tepian.
Ide itu langsung ditempuh. Diam-diam seperti kucing, menunggu dan mengintip.
Seperempat jam kemudian tanah mulai bergetar dan debu yang luar biasa memenuhi udara. Kami belum pernah mendengar gemuruh hentakan langkah gajah sedekat itu.
Mereka tampak berbicara dan tertawa dalam suara serak mereka. Bervariasi. Ada juga yang melengking seperti terompet.
Sepanjang waktu mereka tetap bermain dan berjalan di sekitar halaman kuil dan tidak sampai pagi mereka beristirahat di semak-semak.
Pagi itu aku akan mengingat sepanjang hidupku. Saat matahari terbit, lelah dan menggigil, aku memanjat tepi sungai yang tinggi dan memandang hutan.
Saya bermeditasi. Tidak lama. Lalu mengambil buku catatan dan pergi ke halaman kuil. Ayo, aku akan mengukur gerbang.
***
Ada kisah apa di balik fenomena itu?
Cerita yang disampaikan Izul, nyaris sama dengan apa yang ditulis Schnitger dalam catatannya tahun 1935...
Malays say that the Hindoo ruler was transformed into an elephant, and for this reason great herds of elephants regularly visit the ruins to do homage to the spirit of their departed ancestor.
Bahwa penguasa Hindu di sana ketika meninggal hidungnya berubah panjang jadi belalai, dan telinganya melebar seperti gajah. Karenanya, gajah memberi penghormatan.
Kisah versi itu, apakah hidup di kalangan rakyat setempat, kemudian hari setelah Schnitger menuliskannya? Atau… Entahlah!
Yang pasti, kini, sudah tak ada lagi gajah di Muara Takus.
Awal 1990-an, pemerintah memindahkannya ke arena Pelatihan Gajah Balai Raja di daerah Duri, Riau.
Waktu itu, untuk kepentingan pembangunan PLTA Kota Panjang yang didanai Jepang, 13 desa di dua kecamatan di hulu Sungai Kampar Kanan, yang merupakan habitat hidup gajah ditenggelamkan. Penduduknya direlokasi.
Berdasarkan laporan Friend of River, organisasi lingkungan yang berpusat di Jepang, pemindahan gajah dari Muara Takus ke Duri dilakukan mulai 1993 hingga 1994. Jumlahnya 24 ekor.
Tercerabut dari akarnya, gajah-gajah Candi Muara Takus itu tak berbiak. Bahkan perlahan punah.
“Kini populasi gajah di Duri hanya lima ekor,” kata Ratna Dewi dari WWF Centra Sumatera, kepada JPNN, di Pekan Baru, Senin, 28 Januari 2019.
Begitulah. Cerita pradaksina gajah di Candi Muara Takus tinggal kenangan.
Meski sampai sekarang, orang-orang candi masih berbangga, “di luar sana, gajah (maksudnya patung Ganesha--red) disembah. Di sini, gajah menyembah,” kata Manglin Bungsu, tetua di kawasan Muara Takus. (wow/jpnn)
Di Candi Muara Takus, Riau. Tiap purnama tiba, rombongan gajah datang mengelilingi stupa, dan lalu berlutut. Mereka pradaksina--ritual Buddha.
Redaktur & Reporter : Wenri
- Irjen Herry Dorong Bupati Kampar Terus Mengembangkan Pariwisata Candi Muara Takus
- Kapolda Riau Kunjungi Candi Muara Takus, Ajak Masyarakat Jaga dan Lestarikan Warisan Budaya
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Bangsa Pelupa dan Pemaaf, Sebuah Refleksi Tentang Karakter Kolektif Indonesia
- Sejarah Etnik Simalungun dan Kepahlawanan Rondahaim Saragih
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
 JPNN.com
JPNN.com